Editor's Pick
Mengapa Gender Sangat Penting dalam Mitigasi Krisis Iklim

PANTAU24.COM – Di tengah pemukiman urban Kota Manado, Sulawesi Utara, Malla setiap pagi membagi waktu untuk menyapa halaman belakang rumahnya. Ada lubang biopori di sana, ada juga keranjang takakura buatan tangan kasarnya.
Malla bahkan tidak keberatan untuk menggunting lembaran seng dan menggergaji kayu untuk membuat demplot sederhana untuk tomat, cabai, kangkung, dan anggurnya. Menyapu dedaunan kering yang berguguran dari pohon alpukatnya, sisa makanan dan limbah organik dikumpulnya untuk memberi makan tanah.
Tidak ada yang istimewa dari rutinitas yang telaten ia kerjakan selama 10 tahun terakhir seusai operasi miom yang dialaminya di tahun 2015, apalagi Malla menganggap hal ini adalah bagian yang menyenangkan dari hidupnya mengingat sehari-hari ia bekerja sebagai ASN —namun siapa sangka, tindakan sederhana Malla adalah bagian dari upaya besar mencegah krisis iklim.
Perubahan iklim sering dibicarakan dalam angka dan istilah rumit: emisi karbon, kenaikan suhu global, deforestasi, dan lain-lain. Namun, di balik data dan kebijakan besar, ada kehidupan nyata yang terdampak, dan di antara mereka, perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan beban dari krisis ini. Sekaligus, mereka juga adalah aktor utama yang sering diabaikan dalam narasi penyelamatan bumi.
Yang sering terlewat namun paling penting
Perubahan iklim bukan sekadar masalah lingkungan—ia adalah masalah keadilan. Dan keadilan itu, dalam konteks ini, sangat dipengaruhi oleh peran dan posisi gender. Di banyak wilayah, termasuk Indonesia, perempuan memikul tanggung jawab domestik yang besar: memasak, mengurus anak, mengelola air bersih, hingga merawat lansia. Ketika bencana iklim terjadi—banjir, kekeringan, gagal panen—perempuanlah yang paling pertama harus menyesuaikan diri.
Kita kerap lupa, bahwa krisis iklim bukan hanya soal alam yang mengamuk. Ia menyentuh dapur, ember air, bahkan tubuh perempuan. Di sinilah perspektif gender sangat penting: karena untuk bisa merespon secara adil dan efektif, kebijakan iklim harus menyasar pengalaman dan peran hidup perempuan yang berbeda dari laki-laki.

Bagaimana dunia menempatkan perempuan sebagai aktor strategis?
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UN Women dan UNFCCC Gender Action Plan secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan harus menjadi pemimpin dan pengambil keputusan utama dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perempuan tidak hanya dianggap sebagai pihak rentan, tetapi sebagai agen perubahan yang memiliki pengetahuan lokal, keterampilan bertahan, dan kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup.
Di banyak negara, pendekatan gender dalam kebijakan iklim sudah menjadi mainstream. Misalnya:
- Di Bangladesh, program pengurangan risiko bencana memasukkan perempuan sebagai fasilitator pelatihan dan pemimpin komunitas.
- Di Kenya, program pengelolaan hutan berbasis komunitas dipimpin oleh kelompok perempuan yang diberi akses legal terhadap lahan konservasi.
- Di Kosta Rika, perempuan petani mendapatkan subsidi dan pelatihan khusus dalam pertanian adaptif terhadap iklim.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang kesetaraan, tapi juga efektivitas adaptasi iklim.
Bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia telah menyadari pentingnya peran gender dalam pembangunan, termasuk dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar.
Meski Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki kebijakan responsif gender, banyak program mitigasi iklim masih belum melibatkan perempuan secara substantif sebagai pengambil keputusan. Di tingkat desa dan daerah, perempuan sering hanya dijadikan “penerima manfaat” alih-alih “perancang kebijakan”.
Padahal, perempuan Indonesia—terutama di wilayah adat dan pedesaan—memiliki kekayaan pengetahuan dan praktik yang relevan dengan pelestarian lingkungan. Dari pengetahuan tentang musim tanam hingga cara mengolah hasil hutan non-kayu, perempuan sudah lama melakukan praktik adaptif terhadap iklim. Sayangnya, ini jarang tercatat dan dianggap sah oleh sistem perencanaan formal.
Tindakan-tindakan yang dianggap sepele, tapi berdampak besar
Banyak hal yang dilakukan perempuan sering dianggap “biasa” dan “sepele”—padahal punya dampak langsung pada ketahanan iklim. Memilih memasak dengan bahan lokal, menanam sayur di pekarangan, mengajarkan anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan, hingga memanfaatkan kembali barang bekas adalah contoh nyata.
Di kota Sulawesi Utara, gerakan pembuatan eco enzim yang dipelopori oleh ibu-ibu rumah tangga turut memberikan sumbangsih besar terhadap pengelolaan limbah organik rumah tangga, disamping eko enzim dapat disirkulasikan dalam berbagai macam produk turunan hingga praktik baik oleh Bapelitbangda Kota Manado dalam pengurangan kadar emisi karbon di TPA Sumompo.

Dampak krisis iklim terhadap kehidupan perempuan
Namun, tak bisa dipungkiri—perempuan juga paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ketika sumber air mengering akibat kemarau panjang, mereka harus berjalan lebih jauh, mengorbankan waktu belajar atau bekerja. Ketika banjir melanda, mereka yang pertama mengamankan anak-anak, bahkan rela tidak makan demi anggota keluarga lain.
Dalam hal penghidupan, perempuan yang bergantung pada pertanian skala kecil atau pengolahan hasil laut mengalami kerugian paling besar akibat cuaca yang tak menentu. Harga hasil panen anjlok, nelayan tak bisa melaut—dan dampaknya paling terasa di dapur.
Kesehatan perempuan juga terancam. Di daerah terpencil, meningkatnya suhu dan curah hujan ekstrem meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah dan diare. Di sisi lain, akses layanan kesehatan yang layak untuk perempuan masih terbatas, terutama bagi ibu hamil dan lansia.
Pendidikan anak perempuan pun ikut terganggu. Ketika keluarga harus menghemat biaya akibat hasil panen gagal, anak perempuan sering menjadi yang pertama diminta berhenti sekolah untuk membantu pekerjaan rumah atau merawat adik.
Malla mungkin tidak tahu istilah “mitigasi iklim” atau “adaptasi berbasis komunitas”. Tapi setiap hari, dari kebun kecil di halaman rumahnya, dari cara ia menghemat air, dari cara ia mendaur ulang, ia sedang menyelamatkan bumi dengan caranya sendiri.
Dan mungkin, itu yang sebenarnya paling kita butuhkan: bukan lebih banyak jargon, tapi lebih banyak Malla—perempuan yang dengan diam-diam, menjaga bumi tetap hidup.



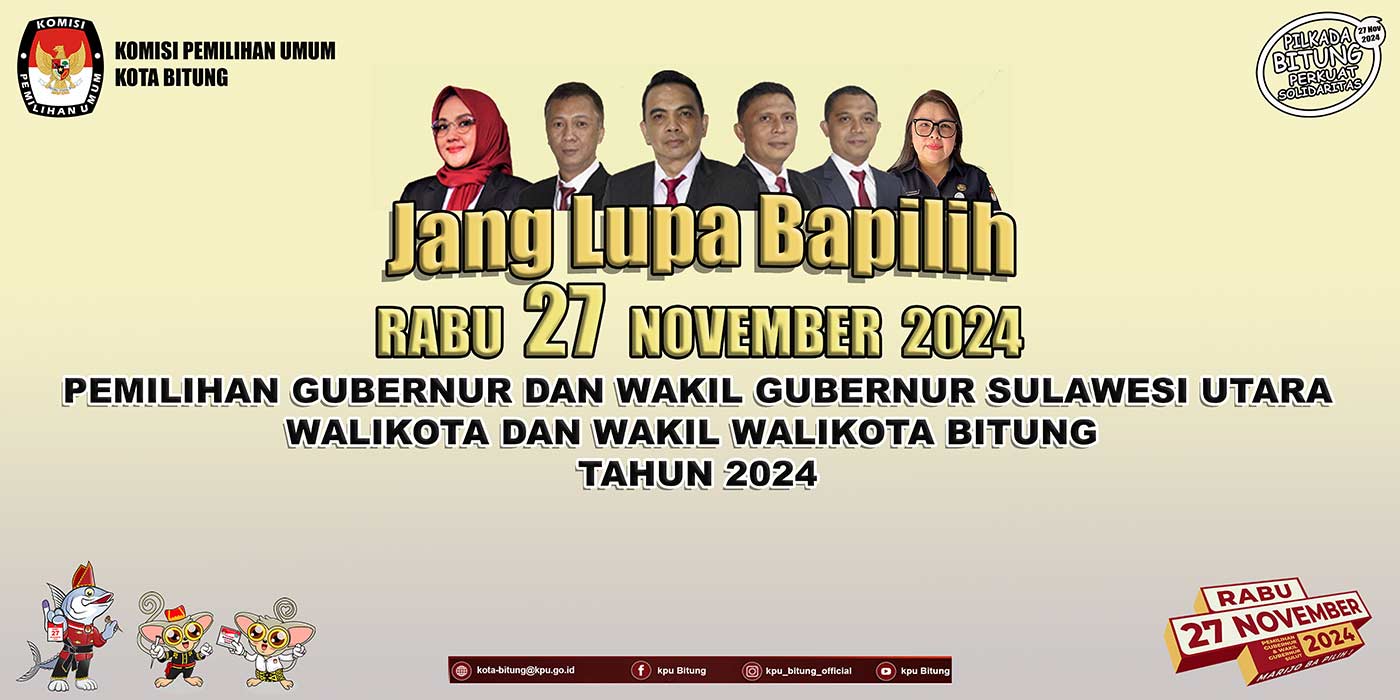



















You must be logged in to post a comment Login