Editor's Pick
Standar bertahan hidup, bukan taraf kesejahteraan

Oleh: Andri Yudhi Supriadi, Badan Pusat Statistik
Bak sudah jadi tradisi, data BPS kerap jadi perbincangan hangat publik, khususnya di linimasa. Terakhir, BPS merilis angka kemiskinan Indonesia per September 2024 hanya sebesar 8,57% dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 24,06 juta jiwa.
Kontroversi mencuat saat Bank Dunia melansir statistik senada dengan hasil yang jauh berbeda: 60% penduduk Indonesia tergolong miskin. Netizen kemudian menyoroti berbagai hal mengenai BPS. Yang disorot mulai dari metode, kredibilitas, hingga motivasi politik di balik kecilnya angka kemiskinan.
Di balik kontroversi ini, sebenarnya seperti apa duduk permasalahan perbedaan angka kemiskinan dari BPS dan Bank Dunia?
Miskin versi BPS
Secara garis besar, BPS menentukan garis kemiskinan berdasarkan dua komponen utama: kebutuhan makanan dan kebutuhan nonmakanan.
Kebutuhan makanan BPS mengacu pada kebutuhan energi minimum 2.100 kilokalori (kcal)/kapita/hari. Artinya, secara statistik orang bisa tergolong “tidak miskin” jika ia mampu memenuhi kebutuhan makanan minimum untuk bertahan hidup dan kebutuhan dasar nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Misalnya, ilustrasi harga bahan makanan pokok (lansiran survei sosial ekonomi nasional) ditentukan sebasar 2.100 kcal/hari adalah Rp440 ribu/bulan, lalu ditambah kebutuhan nonmakanan sekitar Rp150 ribu/bulan. Maka, garis kemiskinannya sekitar Rp590 ribu/bulan/orang, atau sekitar Rp19 ribu/hari/orang dengan asumsi 1 bulan 30 hari.
Penting untuk diketahui bahwa BPS menghitung kemiskinan berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan, bukan per hari. Besarannya pun disesuaikan untuk tiap provinsi, kota, dan desa berdasarkan harga dan pola konsumsi lokal.
Sebagai contoh Kabupaten Tambrauw, Papua Barat menjadi kawasan dengan tingkat konsumsi rumah tangga terendah nasional pada tahun 2024 di angka Rp108 ribu. Adapun Jakarta Timur merupakan kota dengan konsumsi rumah tangga terbesar: di angka Rp558 ribu.
Yang perlu dipahami adalah, batas ini bukan berarti orang yang pengeluarannya Rp600 ribu/bulan (sedikit melebihi Rp590 ribu/bulan) sudah tergolong sejahtera. Garis ini bukan batas sejahtera, tapi batas minimum agar tidak dikategorikan miskin.
Jika ibaratnya batas suhu orang sehat dengan demam yang ditetapkan 38°C sebagai batas kategori orang terjangkit demam. Apakah orang yang suhunya 37,9°C sehat sepenuhnya? Jawabannya bisa iya atau tidak—tergantung persepsi dan intensi tambahan yang akan digunakan.
Acuan Bank Dunia berbeda
Sebagai negara berpendapatan menengah ke atas (Upper Midle Income Country/UMIC), garis kemiskinan versi Bank Dunia untuk Indonesia adalah sebesar $6,85/orang/hari.
Angka ini merupakan median di antara 37 negara UMIC lainnya yang menjadi salah satu acuan perhitungan kemiskinan Bank Dunia. Dari perhitungan ini, munculah 60% penduduk Indonesia terkategori miskin yang memicu perdebatan publik.
Padahal, meski tergolong UMIC, posisi Indonesia masih di batas bawah. Ini terlihat dari pendapatan nasional bruto/PNB per kapita Indonesia sebesar $4.870, dibandingkan rentang PNB negara-negara UMIC saat ini $4.516-$14.005.
Adanya perbedaan tersebut membuat penerapan garis kemiskinan versi Bank Dunia sebesar $6,85 secara langsung di Indonesia cukup beresiko. Apalagi angka kemiskinan Bank Dunia bertujuan untuk melihat posisi negara tersebut di internasional, bukan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.
Kesalahpahaman berikutnya adalah penggunaan kurs nilai tukar pasar untuk mengkonversi garis kemiskinan $6,85 ke dalam rupiah yang seharusnya menggunakan kurs paritas daya beli Purchasing Power Parity (PPP) 2017. PPP ini bukan sistem valuta asing yang mengkonversi nilai satu mata uang dengan mata uang lain dengan skema pasar, tetapi lebih kepada daya beli relatif suatu negara terhadap negara lainnya .
Alhasil, jika batas garis kemiskinan untuk UMIC sebesar $6,85/hari PPP, maka tidak mutlak nilai tersebut setara Rp109,6 ribu/hari sesuai nilai aktual kurs pasar (Rp16 ribu per dolar AS). Bisa saja nilainya turun hingga mencapai Rp41 ribu/hari karena ada penyesuaian indeks daya beli aktual daerah tujuan (menyesuaikan dengan kurs PPP Indonesia Rp5.993/$1).
Tapi sekali lagi, angka kemiskinan ini untuk melihat posisi Indonesia di Internasional bukan untuk implementasi kebijakan. Dengan demikian angka garis kemiskinan Bank Dunia dan BPS memiliki perannya masing-masing dan tidak dapat dicampuradukan.
Di Indonesia, tantangan mengentaskan kemiskinan datang dari urbanisasi cepat, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, serta ketergantungan pada sektor informal (misalnya pedagang kaki lima). Pandemi COVID-19 juga sempat membuat angka kemiskinan naik kembali setelah sempat menurun dalam dekade terakhir.
Bank Dunia mencatat kurs PPP Indonesia terus naik dari tahun ke tahun, dimulai dari Rp4.967,5 pada tahun 2016 menjadi Rp5.993,03 pada tahun 2024. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi antara tahun 2023 ke 2024, yaitu dari Rp5.607,4 menjadi Rp5.993,03. Fluktuasi kurs PPP inilah yang dikalikan oleh ketetapan US$6,85 untuk menetapkan kategorisasi miskin dari Bank Dunia.
Kurs PPP sempat menurun dari tahun 2019 ke 2020, dari Rp5.391,8 menjadi Rp5.386,4, tapi secara umum tetap meningkat. Perubahan nilai kurs PPP ini tidak hanya mencerminkan penyesuaian terhadap daya beli masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada penghitungan angka kemiskinan, khususnya dalam konteks perbandingan internasional.
Nilai ambang kemiskinan global yang dihitung berdasarkan PPP akan berubah seiring dengan fluktuasi acuan ini. Hal tersebut memengaruhi hasil perhitungan jumlah penduduk miskin menurut standar internasional.
Perbedaan angka statistik dengan realita
Salah paham publik terhadap garis kemiskinan bisa berdampak serius. Ketika masyarakat tidak percaya pada data resmi, maka dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan pun bisa lemah. Padahal, data yang kredibel dibutuhkan untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran.
Di sinilah pentingnya literasi data, termasuk literasi media.
Media tidak cukup hanya menulis topik angka kemiskinan turun atau garis kemiskinan sebesar Rp595 ribu, tanpa menjelaskan maknanya. Begitu juga publik yang perlu memahami perbedaan antara angka statistik dan realitas sosial. Keduanya memang berkesinambungan tapi bisa sama tapi tidak selalu sama.
Statistik bukan alat untuk membungkam realita, melainkan instrumen untuk memahami realita lebih baik. Angka kemiskinan bukan soal menyederhanakan penderitaan, tapi tentang mengukur sejauh mana kita telah dan bisa terus memperbaiki hidup masyarakat bersama-sama.
Andri Yudhi Supriadi, Statistisi Ahli, Badan Pusat Statistik
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.



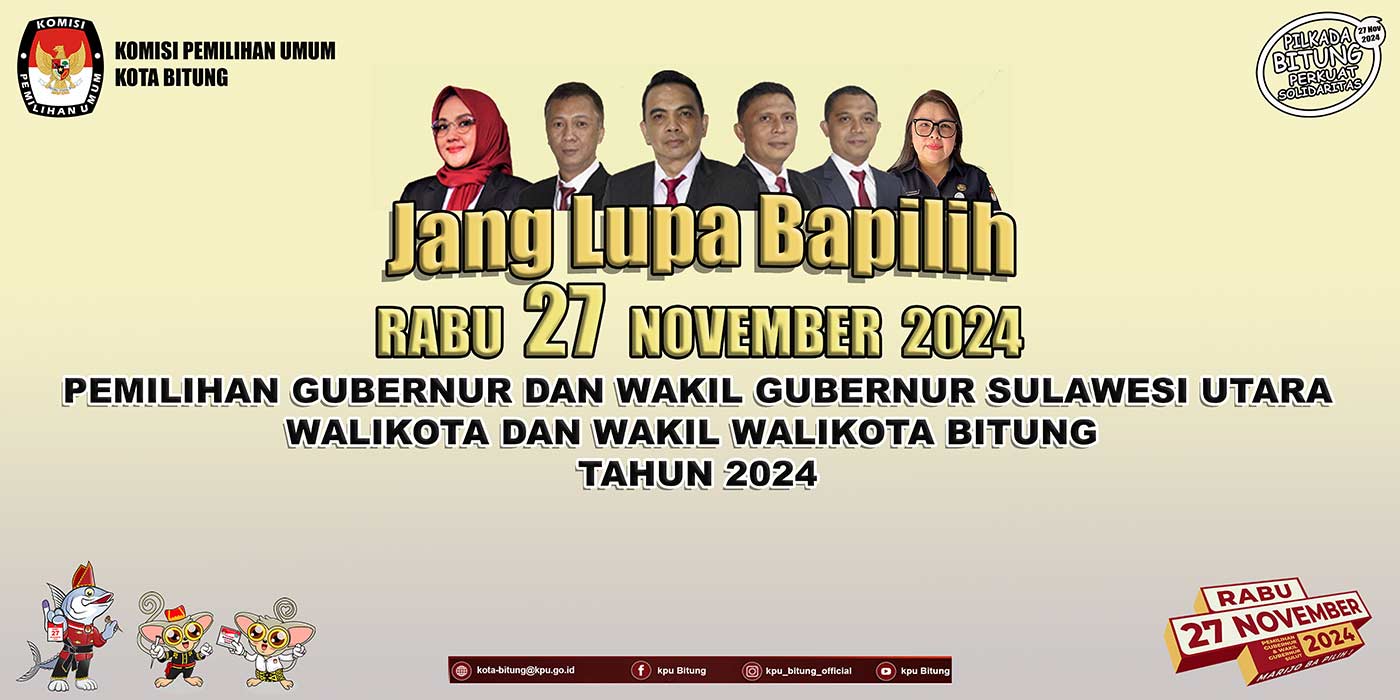



















You must be logged in to post a comment Login